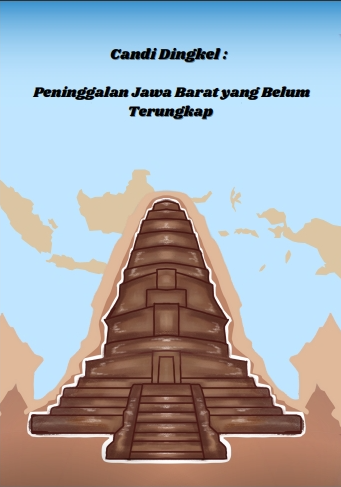Akulturasi Budaya Pada Bangunan Masjid Gedhe Mataram Kotagede
Masjid Gedhe Mataram merupakan masjid tertua
di Yogyakarta, yang dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1640 M. Pembangunan
masjid dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat sekitar yang umumnya
masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Masjid Gedhe Mataram sendiri berada di
kompleks pemakaman raja-raja Mataram yang beralamatkan di Dusun Sayangan,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Pada bagian depan kompleks masjid, terdapat
sebuah prasasti berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat lambang
Kasunanan Surakarta Agung. Ihwal tersebut menunjukan keterlibatan Kasunanan
Surakarta pada tahap kedua pembangunan Masjid Gedhe Mataram, yang dalam hal ini
Paku Buwono X. Perbedaan bangunan yang didirikan oleh Sultan Agung dan Paku Buwono
X adalah pada tiang masjid yang dibangun oleh Sultan Agung berasal dari kayu,
sedangkan Paku Buwono X memakai besi. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang
berbentuk limasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu inti dan serambi.
Kotagede
halaman masjid ke arah lurus dan kanan, terdapat bangunan masjid. Kemudian,
jikalau menuju ke arah kiri, terdapat kompleks makam dan sendang/kolam. Pada
halaman masjid ini berdiri dua buah bangunan Bangsal Pacaosan, yang ada di
sebelah kanan dan kiri halaman. Bangunan Pacaosan berdenah segi empat. Tinggi
lantai 20 cm dari level tanah halaman. Bangsal ini merupakan bangunan terbuka,
tanpa dinding dengan atap berbentuk limasan. Atap disangga oleh kolom kayu
berjumlah enam buah. Pada bagian halaman masjid, juga berdiri bangunan tugu
yang berfungsi sebagai tempat jam/penunjuk waktu salat. Pada puncak tugu, dihiasi
dengan hiasan berbentuk kupluk/peci raja. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan
masjid adalah bangunan milik kerajaan.
menyerupai alun-alun dengan pohon beringinnya, bangunan Pacaosan sebagai
bangunan perantara atau tempat menunggu untuk berkegiatan di Masjid. Menurut
tata ruang Jawa, bangunan Pacaosan digunakan sebagai tempat tunggu, sebelum
masuk ke ruang raja.
Kotagede
ruang dalam. Tata ruang luar terdiri dari pagar pembatas. Pagar pembatas adalah
dinding yang mirip dengan dinding bangunan candi Hindu (Uwarna, 1987). Pada
bagian dalam dinding terdapat jagang/kolam keliling. Jagang mengelilingi
kompleks masjid dan juga ada di sekeliling emper bangunan masjid. Makna jagang
di sekeliling dinding pagar ialah sebagai benteng keamanan (Setyowati, 2007). Akan
tetapi, untuk jagang di sekeliling bangunan masjid digunakan sebagai sarana
membersihkan kaki sebelum masuk ke masjid. Dinding pagar keliling memiliki tiga
buah gapura sebagai pintu masuk. Gapura-gapura ini berbentuk paduraksa, semacam
gapura pada candi. Persis di
bagian depan gapura, akan ditemui sebuah tembok berbentuk huruf “L”. Pada tembok tersebut, juga terpahat beberapa gambar
yang merupakan lambang kerajaan. Bentuk paduraksa dan huruf “L” tersebut
merupakan bentuk toleransi Sultan Agung pada warga Hindu dan Buddha yang ikut
bergotong royong membangun masjid
Kotagede
Masjid Gedhe Mataram juga terdapat pada sisi halaman luar masjid alias area
pekarangan. Pada sisi kiri halaman, akan ditemui pagar tinggi yang terbuat dari
batu bata besar. Pagar tersebut merupakan pagar utama yang dibangun pada masa
Sultan Agung dan merupakan bangunan asli dari Masjid Gedhe Mataram. Konon, perlekatan
dari batu bata ini menggunakan gula aren. Pagar ini dihiasi batuan marmer yang
berukir aksara jawa dan menjadi ciri khas lain dari Masjid Gedhe Mataram. Kemudian
pada sisi kanan halaman, terdapat pagar dengan ukuran batu bata lebih kecil dan
warna yang lebih pucat. Pagar tersebut merupakan hasil pembangunan kedua
oleh Pakubuwono X. Pagar dengan batu bata kecil ini lebih mendominasi keseluruhan
bagian pagar, yang diakhiri dengan pintu gerbang cantik berarsitekturkan
Jawa kuno, paduraksa. Sebuah konsep arsitektur khas budaya Hindu.
Kotagede
dari Masjid Gedhe Mataram. Saka sendiri berfungsi sebagai penyangga bangunan
serambi masjid dengan atap limasan. Sambungan antara atap tajug lambang gantung dengan atap limasan pada serambi menggunakan
talang dari plat besi berbentuk cekung setengah bola. Teknik talang dengan
material besi tersebut merupakan teknologi dari pertukangan Cina. Teknik
terebut juga digunakan pada bangunan Kuil Sam Go Kong di Semarang. Kolom pada
bangunan serambi disebut Soko Pengarep dan Soko Penanggap. Semua saka ditopang
oleh pondasi umpak dari batu alam hitam tanpa ornamen. Bagian atas Soko Pengarep
ditutup dengan papan yang penuh dengan ornamen kaligrafi. Tiang atau saka pada
Masjid Gedhe Mataram dikenal dengan istilah “saka guru”. Istilah tersebut
diambil dari bahasa Sanskerta, yang mana “saka” berarti tiang dan “guru”
berarti utama. Jadi, saka guru merupakan tiang penyangga utama dari Masjid
Gedhe Mataram. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saka guru merupakan
bagian dari unsur Jawa.
sebuah jagang atau kolam yang berbentuk menyerupai parit dan mengelilingi
masjid. Pada awalnya, jagang tersebut terhubung dengan sendang yang berada di
sebelah selatan masjid. Namun, terkait dengan masalah perairan di area masjid,
maka jalan air yang menghubungkan kolam dengan sendang diputus sehingga jagang
berdiri sendiri mengelilingi masjid. Jagang juga pada awalnya digunakan sebagai
media berwudu, membersihkan kotoran sebelum memasuki masjid. Jagang mengandung
filosofi bahwa sebelum memasuki masjid, hendaknya seseorang menghilangkan sifat
angkaranya terlebih dahulu. Lamun seiring dengan berjalannya waktu, atas dasar
pemutakhiran masjid, dibangunlah tempat wudu dengan keran menggantikan fungsi
bersuci dari jagang. Kini, jagang yang mengelilingi Masjid Gedhe Mataram hanya
berfungi untuk mendinginkan masjid.
Kotagede
Mataram ialah terdapat sebuah mustaka di puncak atap masjid. Mustaka tersebut
tidak berornamenkan bulan sabit/lafaz Allah pada umumnya, melainkan sebuah gada
berukuran besar yang berornamenkan daun mimbar. Pada bagian atap masjid,
terdiri dari dua tingkat. Atap masjid Gedhe Mataram Kotagede terbuat dari kayu
dan ditutup menggunakan genteng. Pada bagian atas atap tersebut berbentuk
segitiga dengan sudutnya yang runcing. Kemudian, bagian bawah atap tersebut
seperti segitiga yang terpotong bagian atasnya saja. Pada bagian puncak
tersebut diberi mahkota yang disebut dengan “pataka”.
Mataram Kotagede
berukuran diameter 85 cm. Beduk sebagai penanda waktu salat ini merupakan
hadiah yang diberikan oleh Nyai Pinggit dari Desa Dondong, Kulon Progo. Untuk
mengenang jasa Nyai Pinggit, keturunannya diperbolehkan menempati wilayah di
sekitar area masjid. Daerah tersebut diberi nama Dondongan. Mereka juga menjadi
abdi dalem yang bertugas mengurusi masjid. Masjid Gedhe Mataram juga mempunyai
mimbar khotbah di dalamnya. Mimbar tersebut terletak di sebelah utara mihrab.
Menurut catatan sejarah, mimbar tersebut merupakan pemberian dari Kesultanan
Palembang Darussalam kepada Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung.